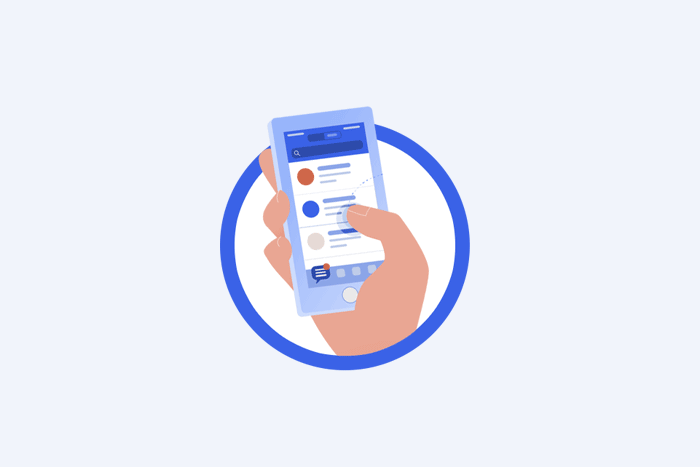Dari Tsunami ke Banjir: PMI dan Ujian Kedua Aceh
ACEH, Desember 2025. Dua puluh satu tahun setelah tsunami 2004, Aceh kembali diuji. Bukan oleh gelombang laut, tapi oleh air bah yang turun dari langit dan gunung. Banjir bandang dan longsor melumpuhkan Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidie, hingga Lhokseumawe. Namun, yang paling menyakitkan bukan hanya rumah yang hanyut atau jalan yang terputus, melainkan kenyataan bahwa negara kembali datang terlambat.
Di tengah kekacauan itu, Palang Merah Indonesia (PMI) bergerak. Bukan sebagai pelengkap seremoni, tapi sebagai jangkar kemanusiaan. Dan di balik gerak cepat itu, berdiri tiga sosok yang tak menunggu aba-aba: Jusuf Kalla, Sudirman Said, dan Ahmad Haiqal Asri.
---
Jusuf Kalla: Logistik, Laut, dan Legitimasi
Dari Jakarta, Jusuf Kalla tak menunggu rapat koordinasi. Ia tahu, dalam bencana, waktu adalah nyawa. Maka ia kirim kapal Kalla Lines, mengangkut 1.500 ton bantuan ke Pelabuhan Krueng Geukuh. Di dalamnya: 11 truk tangki air, logistik pangan, dan perlengkapan darurat. Tak cukup di situ, ia juga mengoordinasikan pengiriman 200.000 butir telur asin lewat pesawat Hercules TNI AU dan kargo BNPB.
Langkah ini bukan sekadar logistik. Ini adalah pernyataan: bahwa PMI bukan subordinat birokrasi, melainkan simpul kemanusiaan yang otonom dan tanggap. JK, yang pernah memimpin rekonstruksi Aceh pascatsunami, kembali hadir bukan dengan pidato, tapi dengan kapal dan keputusan.
“Bagi PMI, bencana adalah bencana. Tidak perlu menunggu status.”
Pernyataan ini menjelaskan mengapa PMI bisa bergerak cepat, bahkan ketika pemerintah masih memperdebatkan apakah banjir ini layak disebut darurat nasional. Bagi PMI, yang penting bukan status, tapi penderitaan yang nyata.
---
Sudirman Said: Dari Musyawarah ke Medan Bencana
Di Takengon, Sudirman Said datang membuka Musyawarah Provinsi PMI Aceh. Tapi musyawarah itu berubah menjadi musibah. Hujan deras memutus jalan, longsor menutup akses, dan perjalanan pulang menjadi ujian nyali. Perjalanan Takengon–Bireuen yang biasanya tiga jam, berubah menjadi sembilan jam penuh rintangan.
“Baru kali ini saya takut sekali dengan suara hujan,” tulisnya. Ia menyebut bencana ini lebih luas dari tsunami 2004—bukan dari jumlah korban, tapi dari sebaran dan keterisolasian.
Sudirman bukan hanya pejabat pusat. Ia adalah penyintas, pengingat, dan penghubung sejarah. Ia membawa ingatan tentang BRR dan tsunami, dan kini menyaksikan bahwa dua dekade setelahnya, negara masih gagap menghadapi bencana. Dalam catatan reflektifnya, ia menulis:
“Kita bisa berencana, tetapi Tuhanlah yang memastikan. Tapi kita juga tahu, Tuhan tak menyukai kelambanan.”
Ia menyerukan agar pejabat “meliburkan dulu politiknya” dan fokus pada kemanusiaan. Seruan yang sederhana, tapi terasa radikal di tengah hiruk-pikuk kekuasaan yang sering tuli terhadap jeritan lumpur.
---
Ahmad Haeqal Asri: Suara dari Wilayah Terisolir
Di Bener Meriah, Ahmad Haiqal Asri, Ketua PMI Banda Aceh, bukan sedang memimpin rapat atau meninjau gudang logistik. Ia terjebak. Bersama relawan dan warga, ia menyaksikan sendiri bagaimana akses darat terputus, BBM habis, dan logistik menipis. Dalam pesan daruratnya, ia menulis:
“Sudah tujuh hari kami terisolir. Warga mulai kelaparan. Kami butuh bantuan udara.”
Haiqal bukan hanya relawan. Ia menjadi saksi dan juru bicara penderitaan. Ia tak menunggu aba-aba dari atas. Ia mengirim sinyal ke luar, menembus kabut birokrasi, agar dunia tahu: Aceh sedang tenggelam, dan waktu adalah musuh.
Ia juga menyuarakan nasib para atlet PORA yang terjebak di Aceh Tengah, menyoroti bagaimana bencana tak hanya merusak rumah, tapi juga merampas ruang hidup, ruang olahraga, dan ruang harapan.
---
Darah yang Mengalir ke Wilayah Terluka
Di tengah lumpur dan reruntuhan, kebutuhan akan darah sering luput dari sorotan. Namun PMI tak lupa. Melalui Unit Donor Darah Banda Aceh, PMI mendistribusikan 1.955 kantong darah ke berbagai rumah sakit di wilayah terdampak: Aceh Timur, Langsa, Lhokseumawe, Aceh Jaya, hingga Aceh Barat.
Mutia, Kepala UDD PMI Banda Aceh, menyebut bahwa darah-darah ini datang dari donor masyarakat di seluruh Indonesia. Mereka tak mengenal siapa yang akan menerima, tapi percaya bahwa setetes darah bisa menyelamatkan nyawa.
Distribusi darah ini bukan hanya soal medis. Ia adalah simbol bahwa PMI hadir sampai ke nadi terdalam bencana. Ketika negara masih sibuk mengukur kerusakan, PMI sudah menjawab kebutuhan yang paling mendesak: mempertahankan hidup.
---
PMI Tulang Punggung Negara Darurat
Tiga sosok ini—JK, Sudirman, Haeqal—mewakili tiga simpul kekuatan PMI: logistik nasional, moral sejarah, dan akar rumput. Di tengah bencana, mereka tak hanya menolong. Mereka menjadi cermin retak yang memantulkan wajah negara: lamban, jauh, dan kadang absen. PMI laksana tulang punggung ketika negara dalam keadaan darurat.
Justru karena itu, PMI menjadi lebih dari sekadar organisasi. Ia menjadi negara darurat, tempat warga menggantungkan harapan, bukan karena mandat, tapi karena kehadiran.
PMI tak punya kewenangan memaksa, tapi ia punya legitimasi moral. Ia tak punya anggaran triliunan, tapi ia punya jaringan relawan yang siap tidur di lumpur. Ia tak punya kekuasaan, tapi ia punya kepercayaan.
---
Ujian Kedua Aceh, Ujian Kedua Kita
Banjir bandang ini adalah ujian kedua bagi Aceh. Tapi ia juga ujian kedua bagi kita semua: apakah kita belajar dari tsunami, atau hanya memperingatinya dengan karangan bunga dan seminar?
PMI telah menjawab ujian ini dengan tindakan. Tapi pertanyaannya: di mana negara? Di mana kementerian yang seharusnya hadir sebelum lumpur mengering? Di mana para pemimpin yang dulu bersumpah tak akan mengulangi kelambanan 2004?
Seperti ditulis Kompas, “Mualem seperti berjalan sendirian.” Tapi ia tidak sendiri. Ada PMI. Ada relawan. Ada warga yang saling mengangkat puing dan harapan.
Dan Aceh, yang pernah menjadi pusat luka nasional, kini kembali mengingatkan kita: bahwa kemanusiaan bukan soal struktur, tapi soal siapa yang datang lebih dulu, dan siapa yang tetap tinggal ketika air mulai surut. (acehtrend.com)